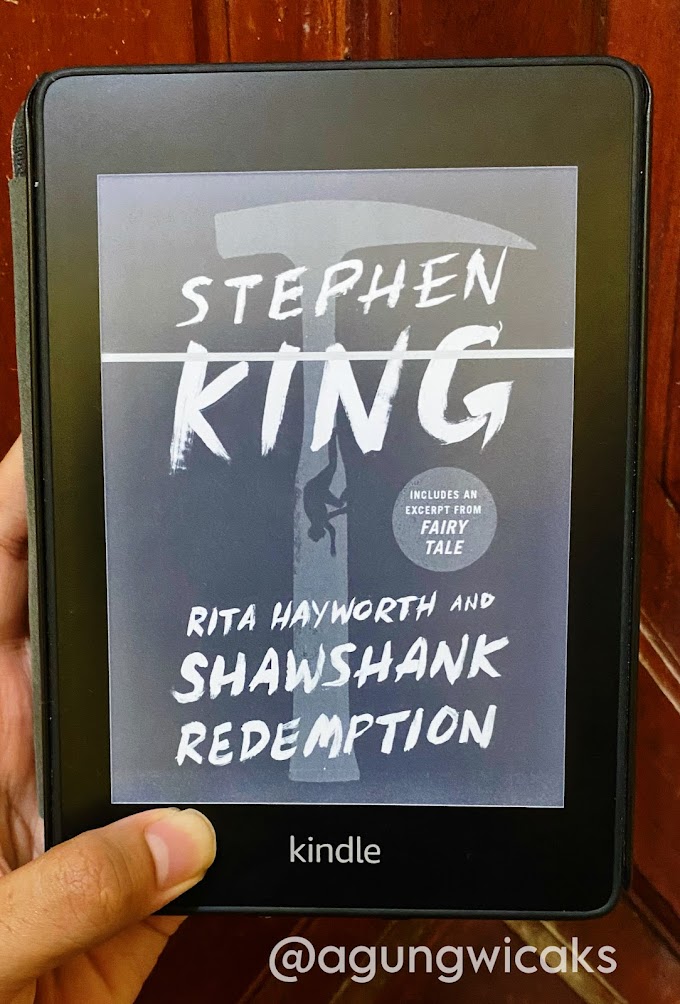Ilustrasi unjuk rasa.
(Sumber gambar: freepik.com)
Pada 28 Agustus 2025, peristiwa tragis terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, di mana kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri melindas seorang pengemudi ojek daring bernama Affan hingga tewas selama pengendalian unjuk rasa. Kendaraan lapis baja tersebut melaju cepat di tengah kerumunan massa yang sedang berunjuk rasa menuntut kesejahteraan buruh, seperti penghapusan tenaga alih daya dan kenaikan upah minimum. Respons polisi pasca-peristiwa mencakup pemeriksaan terhadap tujuh anggota Brimob oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, janji transparansi, dan permintaan maaf dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Adi Suheri. Namun, sikap polisi dalam kasus ini patut dikritik secara serius, karena mencerminkan pola berulang kekerasan berlebihan, kurangnya akuntabilitas, dan respons yang lebih reaktif daripada preventif. Kritik ini tidak hanya berdasarkan peristiwa tunggal, melainkan juga konteks historis kekerasan polisi selama unjuk rasa di Indonesia, yang sering kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia (HAM).
Pola Kekerasan Berulang dan Kurangnya Pencegahan
Sikap polisi pada peristiwa Pejompongan menunjukkan kegagalan dalam mencegah kekerasan, meskipun ada peringatan dari pihak eksternal seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang meminta aparat bertindak dengan "penuh kehati-hatian" saat menangani unjuk rasa. Penggunaan kendaraan taktis seperti rantis Brimob di tengah kerumunan massa yang relatif damai, seperti demo buruh yang menuntut revisi UU Pemilu dan RUU Perampasan Aset, merupakan bentuk eskalasi yang tidak proporsional. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan tersebut tidak hanya menabrak, tetapi juga melindas korban yang berupaya lari, sehingga menimbulkan pertanyaan: apakah ini kecelakaan atau tindakan sengaja untuk membersihkan jalan? Reaksi publik di platform X menunjukkan kemarahan luas, dengan banyak pengguna menyebutnya sebagai "brutalitas" dan menuntut pertanggungjawaban penuh, bukan hanya permintaan maaf.
Lebih lanjut, peristiwa ini bukanlah kasus yang terpisah, melainkan bagian dari pola kekerasan polisi selama unjuk rasa di Indonesia. Laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat bahwa antara Juli 2024 hingga Juni 2025, terdapat 602 peristiwa kekerasan oleh oknum polisi, termasuk penembakan dan pemukulan terhadap demonstran [1]. Amnesty International juga mendokumentasikan ratusan korban kekerasan polisi selama demo Hari Buruh Internasional 2025, di mana polisi menggunakan gas air mata dan meriam air secara berlebihan, bahkan terhadap aksi damai [2]. Pada demo tolak revisi UU Pilkada tahun 2024, kekerasan serupa terjadi, dengan polisi melakukan aksi represif yang dikecam sebagai "repetisi brutalitas" [3]. Sikap polisi yang sering mengklaim "kesabaran" ketika menghadapi demonstran (seperti pada kasus demo tolak Omnibus Law 2020) kontras dengan fakta lapangan, di mana kekerasan justru menjadi alat utama pengendalian [4]. Pada konteks ini, janji Kapolri untuk "mengusut" peristiwa Pejompongan terdengar banal, karena kasus-kasus sebelumnya seperti kekerasan pada Hari Buruh 2025 sering mandek di tingkat internal polisi tanpa resolusi yang adil [5].
Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Meskipun Propam Polri memeriksa tujuh anggota Brimob dan melibatkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal, sikap polisi masih patut dikritik karena cenderung melindungi institusi daripada mencari keadilan. Abdul Karim, Kepala Divisi Propam, menyatakan bahwa pemeriksaan sedang dilakukan tetapi belum bisa memastikan peran masing-masing pelaku, meski ketujuhnya berada dalam satu kendaraan. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses internal akan berlarut-larut, seperti kasus-kasus sebelumnya ketika laporan kekerasan polisi terhadap jurnalis atau demonstran selama demo UU Cipta Kerja tidak ditindaklanjuti secara tegas [6]. Permintaan maaf dari Kapolri dan Kapolda, yang menjanjikan "tindak tegas" dan "transparansi", sering kali hanya retorika. Di platform X, salah satu warganet menuntut hukuman mati bagi pelaku, mengkritik bahwa "minta maaf tidak mengembalikan nyawa korban" [7]. Bahkan, perwakilan Brimob mengklaim peristiwa itu "tidak sengaja", sehingga kontradiktif dengan video yang menunjukkan kendaraan melaju kencang dan tanpa ragu melindas tubuh korban [8].
Sikap ini memperburuk kepercayaan publik terhadap polisi sebagai pengayom masyarakat. Pada unjuk rasa buruh 2025, massa menuntut hak ekonomi dan reformasi politik untuk mencegah korupsi aset, yang ironisnya dibayangi oleh kekerasan aparat yang seharusnya melindungi. Amnesty International menyoroti "lubang hitam pelanggaran HAM" di mana setidaknya 579 orang menjadi korban kekerasan polisi selama periode 2024, sebagian besar saat menghadapi unjuk rasa [9]. Tanpa akuntabilitas eksternal yang kuat, seperti pengadilan independen daripada hanya Propam, sikap polisi akan terus mempertahankan impunitas.
Dampak Sosial
Peristiwa ini memiliki dampak luas: hilangnya nyawa Affan, seorang pengemudi ojek daring yang tak bersalah, memicu aksi solidaritas dari rekan-rekannya untuk mendatangi Mako Brimob dengan tujuan menuntut keadilan [10]. Di X, tagar seperti #StopPoliceBrutality dan kritik "ACAB" (All Cops Are Bastards) mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap institusi yang seharusnya melindungi. Secara lebih luas, kekerasan ini menghambat hak berekspresi dan berkumpul, yang dijamin konstitusi, serta memperburuk ketegangan sosial di tengah tuntutan buruh yang sah.
***
Sikap polisi pada peristiwa Pejompongan (dari penggunaan kekerasan berlebihan sampai respons yang terkesan hanya formalitas) layak dikritik sebagai manifestasi dari masalah struktural dalam institusi kepolisian Indonesia. Meskipun ada janji transparansi dan pemeriksaan, rekam jejak menunjukkan bahwa tanpa reformasi yang serius (seperti penguatan pengawasan eksternal, pelatihan pengendalian massa yang berbasis HAM, dan penghapusan impunitas) pola kekerasan akan berulang. Pemerintah dan Polri harus belajar dari kritik ini untuk membangun kepercayaan publik, bukan hanya meminta maaf setelah nyawa melayang. Hanya dengan akuntabilitas sejati, polisi bisa benar-benar menjadi pengayom, bukan ancaman bagi rakyat.
________________
Sumber: