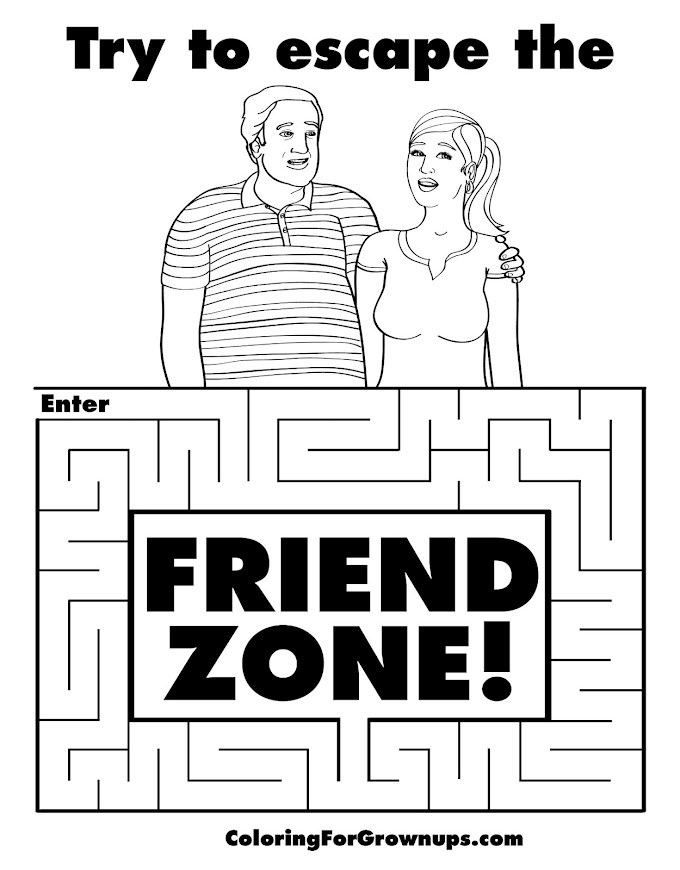Ilustrasi tentang cinta yang tak berbalas.
(Sumber gambar: freepik.com)
Aku menatap layar ponselku, jari-jariku melayang di atas keyboard virtual, ragu untuk menekan tombol kirim. Pesan yang baru saja kuketik sudah terhapus tiga kali, dan setiap kali aku mengetik ulang dengan kata-kata berbeda, getaran di dadaku tetap sama. Aku ingin bertanya padanya, tapi ada sesuatu yang menahan—seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja, atau mungkin harapan yang terlalu rapuh untuk disentuh. Akhirnya, dengan napas tertahan, aku mengetik pesan sederhana: "Kamu di mana?" Lalu, aku menekan tombol kirim sebelum pikiranku sempat menariknya kembali.
Ponselku terdiam di tanganku. Aku menunggu, menghitung detik dalam keheningan kamar yang hanya dipenuhi suara kipas angin tua di sudut. Biasanya, ia membalas cepat, dengan emotikon konyol atau kalimat pendek yang membuatku tersenyum tanpa sadar. Tapi kali ini, menit berlalu, dan layar tetap kosong. Aku meletakkan ponsel di atas meja, berusaha mengalihkan perhatian ke tumpukan buku catatan di depanku, tapi jari-jariku malah memainkan pulpen, memutar-mutarnya hingga tinta bocor dan meninggalkan noda kecil di kertas. Pikiranku melayang—mungkin ia sibuk, mungkin ada yang lebih penting dariku di sana. Atau mungkin, ia sudah tidak peduli.
Malam itu, aku berbaring di ranjang sempitku, memutar lagu lama dari earphone yang sudah usang. Gitarnya pelan, liriknya menusuk, seolah-olah seseorang merangkai kata-kata itu dari perasaanku sendiri. Aku menutup mata, dan wajahnya muncul—senyumnya yang miring, matanya yang selalu menyimpan sesuatu yang tak bisa kutebak. Aku membenci betapa seringnya aku memikirkannya, betapa aku tak bisa mengusir bayangnya dari kepalaku, bahkan saat aku tahu ia mungkin sedang tertawa bersama orang lain di suatu tempat yang tak bisa kuraih.
Keesokan harinya, aku bangun dengan lingkaran hitam di bawah mata dan ponsel yang masih bisu. Aku memaksakan diri berangkat ke kampus, berjalan menyusuri jalan kecil yang dipenuhi pedagang kaki lima dan aroma gorengan. Di kelas, aku duduk di barisan belakang, mencorat-coret margin buku catatan dengan gambar-gambar tak jelas, sementara dosen berbicara tentang sesuatu yang tak kuingat. Pikiranku terus kembali padanya, seperti jarum jam yang macet di angka yang sama.
Saat istirahat, aku duduk sendirian di bangku kayu di halaman kampus, memainkan sisa roti di tanganku. Tiba-tiba, suara tawa yang kukenal mengiris udara. Aku menoleh, dan ia ada di sana—berdiri di dekat pohon akasia, dikelilingi teman-temannya. Jaket biru tua yang selalu ia pakai tampak sedikit kusut, tapi ia tersenyum lebar, tangannya bergerak lincah saat menjelaskan sesuatu. Hatiku bergetar, dan aku merasa wajahku memanas. Aku ingin berjalan ke sana, menyapanya, tapi kakiku terpaku. Aku hanya bisa menatap, diam-diam berharap ia menoleh dan melihatku. Tapi ia tidak melakukannya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dan aku merasa seperti bayangan yang tak pernah ia sadari.
Aku meninggalkan halaman itu dengan langkah cepat, menunduk agar tak ada yang melihat mataku yang mulai berkaca. Di dalam toilet kampus, aku membasuh wajahku, menatap cermin, dan berbisik pada diri sendiri untuk berhenti bertingkah bodoh. Tapi cermin itu tak bisa menjawab kenapa aku begitu lelet melepaskan sesuatu yang bahkan tak pernah kumiliki.
Malam terus berganti, dan aku masih terjebak dalam lingkaran yang sama. Setiap kali ponselku berbunyi, aku meraihnya dengan cepat, berharap itu dia, tapi kebanyakan hanya notifikasi tak penting atau pesan dari teman sekelas yang bertanya tugas. Aku mulai membenci diriku sendiri—kenapa aku begitu terpaku padanya? Kenapa aku tak bisa berhenti memutar lagu itu, lagu yang membuatku membayangkan ia di setiap nadanya?
***
Suatu malam, aku pergi ke sebuah acara kecil di rumah temanku, sebuah reuni dadakan dari geng SMA. Aku berharap keramaian bisa mengusir bayang-bayangnya dari kepalaku. Di sana, lampu-lampu gantung murah berkedip pelan, dan musik diputar terlalu keras hingga aku harus berteriak untuk bicara. Aku memegang gelas plastik berisi minuman soda yang tinggal sedikit, berusaha ikut tertawa saat temanku bercerita tentang kejadian lucu di kelas dulu. Namun di tengah keriuhan itu, aku merasa hampa.
Lalu, aku melihatnya. Ia berdiri di dekat meja makanan, memegang sepotong kue cokelat, berbicara dengan seseorang yang tak kukenal. Rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya bersinar di bawah cahaya lampu. Aku menahan napas, gelas di tanganku hampir terlepas. Ia menoleh, dan tatapan kami bertemu. Untuk sesaat, dunia seolah terhenti—tidak ada musik, tidak ada suara tawa, hanya ia dan aku. Ia tersenyum kecil, dan aku merasa lututku lemas. Aku membalas senyumnya, meski aku yakin wajahku pasti terlihat kaku.
Ia berjalan mendekat, dan aku mencium aroma samar parfumnya yang bercampur dengan udara malam.
"Nggak nyangka ketemu kamu di sini," katanya, suaranya lembut tapi cukup jelas di tengah kebisingan.
"Aku diundang," jawabku, mencoba terdengar santai, padahal tanganku berkeringat. "Kamu?"
"Sama," katanya, lalu tertawa pelan. "Udah lama nggak ngobrol, ya?"
Aku mengangguk, tak tahu harus bilang apa. Kami bicara sebentar tentang hal-hal kecil—kampus, teman lama, cuaca—tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membuatku ingin bertanya lebih, ingin tahu apakah ia pernah memikirkanku seperti aku memikirkannya. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut lagi, seseorang memanggilnya dari kejauhan. Ia melirik ke arah sana, lalu menatapku dengan ekspresi menyesal. "Aku balik dulu, ya. Senang ketemu kamu."
Ia pergi, dan aku berdiri di sana, memandangi punggungnya yang menghilang di antara kerumunan. Aku meninggalkan reuni lebih awal, berjalan pulang dengan langkah gontai, dan malam itu, aku bermimpi tentangnya—kami duduk bersama, tertawa, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar ada di sampingku. Tapi pagi datang, dan mimpi itu menguap, meninggalkan rasa sesak yang terlalu nyata.
Aku tak bisa terus begini. Ketidakpastian ini seperti duri yang tersangkut di tenggorokan, tak bisa ditelan, tak bisa dikeluarkan. Aku harus tahu, meski jawabannya mungkin akan menghancurkanku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku dan mengetik: "Kita bisa ketemu nggak? Aku mau ngomong sesuatu." Aku menekan kirim sebelum keberanianku lenyap.
Beberapa menit kemudian, ia membalas: "Bisa. Kapan? Di mana?" Aku menyarankan taman kecil di dekat kampus, tempat yang sepi dengan bangku-bangku kayu tua dan pohon-pohon rindang. Ia setuju, dan kami janjian sore hari.
Malam sebelumnya, aku hampir tak tidur. Aku mondar-mandir di kamar, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku ingin jujur, tapi aku takut ia akan mundur, takut ia akan melihatku berbeda. Tapi aku sudah muak bersembunyi di balik senyum pura-pura dan pesan singkat yang tak pernah mengatakan apa-apa.
***
Sore itu, aku tiba lebih awal. Angin bertiup pelan, membawa aroma rumput basah dari hujan pagi tadi. Aku duduk di bangku, memainkan ujung jaketku, dan menatap setiap orang yang lewat, berharap itu dia. Akhirnya, ia muncul—berjalan dengan langkah santai, tangannya dimasukkan ke saku celana. Ia tersenyum saat melihatku, dan aku merasa sedikit tenang, meski jantungku masih berpacu.
"Apa kabar?" tanyanya, duduk di sampingku.
"Baik," jawabku, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku cuma... aku pengen ngomong sesuatu."
Ia memandangku, alisnya sedikit terangkat. "Apa?"
Aku menunduk sebentar, mencari keberanian, lalu menatap matanya. "Aku menyukaimu. Bukan cuma sebagai teman. Dan aku pengen tahu... kamu ngerasa gitu juga nggak?"
Hening. Angin berdesir di antara kami, dan aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ia menatapku lama, matanya mencari sesuatu di wajahku. Lalu, ia menghela napas pelan. "Aku... aku nggak yakin," katanya, suaranya hampir seperti bisik. "Aku senang denganmu, tapi aku nggak tahu apakah itu sama kayak yang kamu rasain."
Aku merasa dadaku dipukul, tapi aku memaksakan senyum. "Oh. Ya udah, nggak apa-apa. Aku cuma pengen kamu tahu."
Dia mengangguk, tangannya memainkan ujung lengan bajunya. "Makasih udah jujur. Aku nggak mau kita jadi canggungan gara-gara ini."
"Aku juga enggak," kataku, meski aku tahu itu bohong. Akan ada sesuatu yang berubah, meski kami berdua pura-pura tidak.
Kami duduk sebentar lagi, bicara tentang hal-hal ringan, tapi udara terasa tebal. Akhirnya, ia berdiri, mengatakan ada janji lain. Aku mengangguk, melihatnya pergi, dan aku tetap di bangku itu, menatap pohon-pohon yang bergoyang pelan.
***
Malam itu, aku memutar lagu yang sama, tapi kali ini aku tak menangis. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, dan menatap plafon. Aku kecewa, tapi ada sedikit lega di dadaku—aku sudah melangkah, sudah melepaskan kata-kata yang selama ini menggantung di ujung lidahku. Ia mungkin tak merasakan apa yang kurasakan, tapi setidaknya aku tak lagi terjebak dalam bayang-bayang harapan kosong.
Hari-hari berikutnya, aku mulai membiasakan diri. Aku masih melihatnya di kampus kadang-kadang, masih merasakan getar kecil di hati, tapi aku tak lagi menunggu. Aku mengisi waktu dengan teman-teman, dengan buku, dengan hal-hal kecil yang dulu kulupakan. Dan perlahan, bayangnya mulai memudar, walau tak pernah benar-benar hilang.
Mungkin suatu hari ia akan kembali, dengan perasaan yang sama. Mungkin tidak. Tapi aku tak akan menahan napas untuk itu. Aku akan jalan terus, membiarkan waktu melakukan tugasnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa itu cukup.