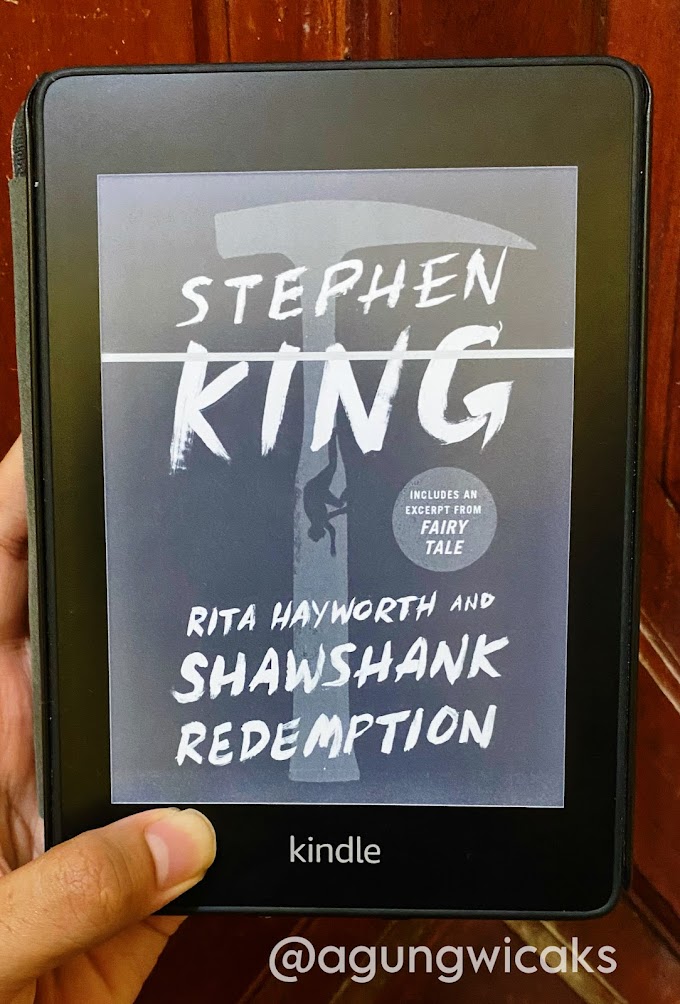Agustinus Wibowo (yang pertama saya kenal lewat bukunya yang berjudul Titik Nol) kembali menyuguhkan sebuah kumpulan esai dan cerita dalam buku Jalan Panjang untuk Pulang (2021). Selain sebagai catatan perjalanan, buku ini merupakan refleksi mendalam tentang makna "pulang" dan identitas diri di tengah dunia yang semakin terhubung tetapi penuh konflik. Diterbitkan setelah rentang waktu penulisan antara 2008 hingga 2020, buku ini mengumpulkan tulisan-tulisan yang pernah dimuat di berbagai media, baik dalam maupun luar negeri, serta catatan baru yang belum pernah dipublikasikan. Melalui lensa pengalaman pribadinya, Agustinus mengajak pembaca menjelajahi destinasi fisik dan perjalanan batin yang membawa kita lebih dekat pada makna kemanusiaan.
Tema utama yang menonjol dalam buku ini adalah perpaduan antara perjalanan dan kepulangan. Agustinus tidak membawa pembaca ke tempat-tempat wisata yang nyaman atau indah secara konvensional; sebaliknya, ia menyoroti wilayah perbatasan, zona konflik, dan masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan identitas mereka. Dari Afghanistan sampai Papua Nugini, dari Kazakhstan sampai Suriname, setiap cerita mengungkap lapisan-lapisan konflik seperti sentimen ras, agama, kemiskinan, dan trauma sejarah. Misalnya, dalam esai 'Terlahir Kembali dengan Roh Berbeda', Agustinus mengandaikan perjalanan imajiner Xu Xiake, seorang musafir Cina kuno, yang jika hidup hari ini akan melihat bagaimana Gunung Huangshan berubah dari tempat isolasi menjadi destinasi wisata massal. Di sini, ia merefleksikan bagaimana manusia membentuk dan dibentuk oleh perubahan lingkungan, serta bagaimana identitas terbentuk melalui interaksi dengan tempat. Begitu pula dengan cerita tentang laki-laki Kazakhstan yang mengaitkan identitasnya dengan elang dalam esai 'Para Pemburu Elang', di mana burung itu bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan simbol tradisi dan kebanggaan yang tak tergantikan.
Gaya penulisan Agustinus menjadi kekuatan utama buku ini. Ia mahir dalam mengamati detail-detail kecil dan merangkainya menjadi narasi filosofis. Sebuah contoh yang mencolok adalah observasinya tentang arsitektur tradisional Huizhou di Xidi, Huangshan:
"Rumah-rumah di sini dibangun dengan tembok tinggi, terlihat dingin dan datar. Mereka memegang teguh prinsip hidup yang sangat implisit, tidak memamerkan kekayaan mereka sedikit pun terhadap orang luar…. Tengoklah juga bagaimana rumah-rumah di sini tidak memiliki jendela… Ini karena para pemuda dari keluarga saudagar melanglang buana mengeruk kekayaan, sehingga yang tertinggal di rumah hanyalah orang tua dan anak-anak."
Kutipan ini tidak hanya menggambarkan fisik bangunan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai privasi, ketertutupan, dan adaptasi terhadap turisme modern. Agustinus hati-hati dalam menyajikan fenomena tanpa mendikte nilai, meninggalkan ruang bagi pembaca untuk menarik kesimpulan sendiri. Setiap esai sering diakhiri dengan punchline reflektif yang kuat, meninggalkan kesan mendalam, meskipun buku ini terasa agak berat di awal karena perpindahan subjek yang cepat.
Beberapa esai menjadi sorotan khusus karena kedalamannya dalam mengeksplorasi identitas. Esai 'Garis Batas di Atas Kertas' membahas dinamika perbatasan di Asia Tengah, seperti enclave Vorukh di Tajikistan yang dikelilingi Kyrgyzstan, di mana penduduk baru menyadari status mereka setelah puluhan tahun (ilustrasi bagaimana identitas nasional bisa begitu cair). Lainnya, seperti 'Dunia di Mata Mereka yang Tidak Bepergian', merefleksikan pandangan orang-orang yang tak pernah meninggalkan kampung halaman mereka, sementara 'Bendera Merah Putih di Garis Batas' menyentuh isu nasionalisme di perbatasan Indonesia. Esai 'Laut' menyentuh secara emosional, di mana Agustinus dan ayahnya memaknai identitas Cina mereka secara berbeda, menunjukkan bahwa identitas yang sama bisa diinterpretasikan secara personal. Tak ketinggalan, esai 'Seorang Pencari dan Napasnya' mengungkap perjalanan batin Agustinus melalui meditasi untuk menghadapi gejolak dalam diri, sementara 'Melihatnya dari Sisi Berbeda' tentang perosotan warna-warni di Katedral Norwich mengajak pembaca memikirkan ulang konsep Tuhan melalui kepolosan anak kecil:
"Tuhan pasti juga mencintai aku karena aku pakai baju warna-warni pelangi."
Pada akhirnya, Jalan Panjang untuk Pulang bukan tentang petualangan fisik semata, melainkan perjalanan menuju kemanusiaan dan kedamaian batin. Agustinus menekankan bahwa pulang bisa berarti kembali ke rumah, tanah air, negeri leluhur, diri sendiri, atau bahkan Tuhan. Buku ini mengingatkan kita bahwa di tengah globalisasi, pertanyaan tentang identitas semakin relevan. Seperti yang dikemukakan dalam salah satu refleksi:
"Perjalanan adalah proses yang spiritual, yang meditatif, yang melucuti ego dan menjadikan kita sebagai musafir yang bukan siapa-siapa. Justru pada saat menjadi bukan siapa-siapa itulah, kita akan mengalami masa-masa yang paling bahagia."
Membaca buku ini secara perlahan memungkinkan pembaca menyadari betapa dangkal pemahaman kita tentang keberagaman, dan mendorong untuk "pulang" ke empati dan kesederhanaan sebagai makhluk sosial.
Dalam konteks sastra perjalanan Indonesia, buku ini menarik karena fokusnya kepada manusia bukan destinasi, serta kemampuannya membangkitkan emosi seperti ketegangan, kemarahan, dan haru. Selain untuk melihat dunia, Agustinus Wibowo meminjamkan matanya untuk menyelami makna, mengajak kita semua menempuh jalan panjang itu: menuju pemahaman yang lebih hakiki tentang siapa kita sebenarnya.