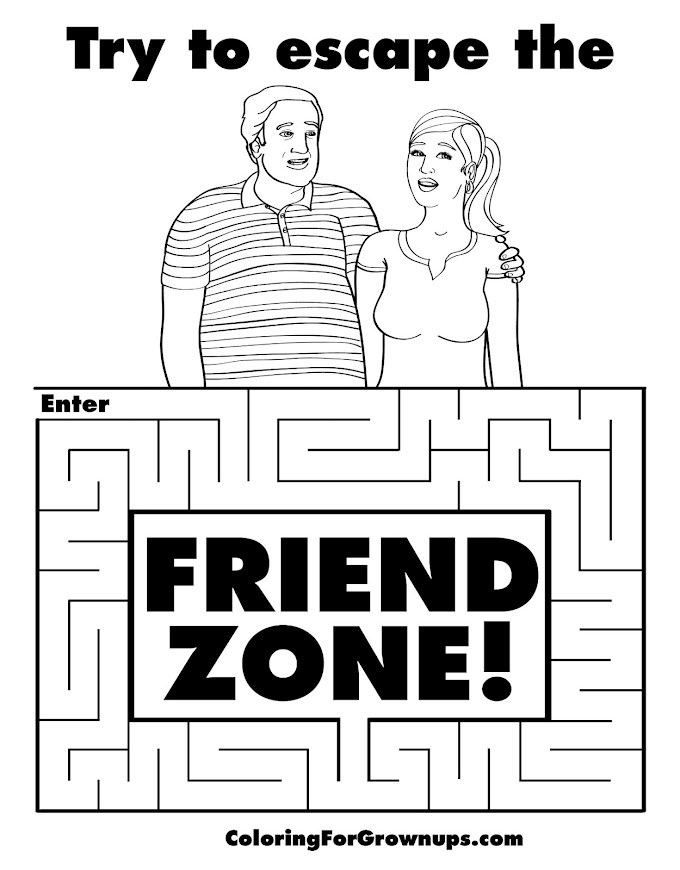Ilustrasi seorang perempuan dan lelaki yang sedang putus cinta.
(Sumber gambar: freepik.com)
Adi menatap ke arah kerumunan, jantungnya berdegup kencang saat matanya menangkap sosok yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Dinda berdiri di sana, di tengah tawa dan irama musik yang menggema, rambutnya berkibar lembut tertiup angin malam. Senyumnya lebar, matanya berbinar—seperti dulu, tapi kali ini bukan untuk Adi. Ia menelan ludah, rasa sesak menyelinap di dadanya. Sudah berapa lama ia tidak melihat Dinda? Dan mengapa, setelah semua yang ia lakukan, bayangan air mata di mata Dinda masih mampu membuatnya ingin berlari mendekat?
Festival musik tahunan di kota kecil itu ramai seperti biasa. Orang-orang berdesakan di depan panggung, menari dan bernyanyi mengikuti lagu-lagu yang dimainkan band lokal. Adi berjalan perlahan, tangannya terkepal di saku jaket. Ia tidak berencana datang malam ini, tapi Genta, sahabatnya, bersikeras mengajaknya. “Lu harus keluar, Di. Jangan cuma ngurung diri di rumah,” katanya tadi siang. Adi akhirnya setuju, meski hatinya berat. Dan sekarang, di tengah lautan manusia ini, ia melihat Dinda. Bukan kebetulan yang ia harapkan, tapi yang ia takutkan.
Langkahnya terhenti saat Dinda tiba-tiba berbalik. Mata mereka bertemu. Senyum di wajah Dinda memudar seketika, digantikan oleh ekspresi yang sulit dibaca—kejutan, mungkin, atau sesuatu yang lebih dalam. Adi melihat kilatan di mata Dinda, lalu setetes air mata mengalir di pipinya. Dinda cepat mengusapnya dengan punggung tangan, tapi Adi tahu apa yang dilihatnya. Ia tahu, karena ia pernah menjadi penyebab air mata itu, berulang kali.
“Dinda,” panggil Adi, suaranya hampir tenggelam oleh dentuman bass dari panggung. Ia melangkah mendekat, tapi Dinda memalingkan wajah, pura-pura tidak mendengar. “Dinda, tunggu.”
Dinda berhenti, tapi tidak menoleh. “Adi,” jawabnya pelan, nada suaranya datar. “Aku baik-baik aja. Nggak usah khawatir.”
Adi tergagap. Ia ingin mengatakan sesuatu—apa saja—tapi kata-kata terasa macet di tenggorokan. “Aku... aku cuma mau ngobrol. Sebentar aja.”
Dinda akhirnya menatapnya, matanya dingin. “Ngobrol apa? Udah nggak ada yang perlu dibahas, kan?” Ia berbalik, bergabung kembali dengan teman-temannya yang masih asyik menikmati musik. Adi hanya bisa berdiri di sana, merasakan hawa dingin menyelinap di antara keramaian yang hangat.
Malam itu, Adi duduk di bangku kayu di pinggir area festival, tangannya memainkan botol air mineral yang sudah kosong. Genta muncul dari kerumunan, wajahnya penuh tanya. “Lu kenapa, Di? Muka lu pucet banget.”
Adi menghela napas panjang. “Gue ketemu Dinda tadi. Dia... dia kelihatan bahagia banget, Gen. Tapi pas lihat gue, dia nangis. Cuma bentar, tapi gue lihat.”
Genta duduk di sampingnya, alisnya berkerut. “Lu yakin itu bukan cuma perasaan lu?”
Adi menggeleng. “Nggak. Gue tau itu nyata. Dan gue ngerasa bersalah banget. Gue yang nyakitin dia, gue yang pergi. Sekarang gue nyesel, tapi kayaknya udah nggak ada gunanya.”
Genta menepuk pundak Adi. “Lu pernah bilang lu pergi karena lu takut, kan? Takut sama hubungan yang serius. Tapi Dinda nggak salah apa-apa, Di. Dia cuma nyoba bahagia lagi.”
Kata-kata Genta seperti pisau yang menusuk perlahan. Adi menunduk, mengingat malam setahun lalu saat ia memutuskan hubungan dengan Dinda. Ia tidak memberikan alasan jelas—hanya bilang ia butuh waktu, butuh ruang. Tapi sebenarnya, ia lari. Dari komitmen, dari rasa takut kehilangan dirinya sendiri. Dan sekarang, melihat Dinda yang mulai pulih, ia justru merasa kehilangan.
“Gue harus ngomong sama dia, Gen,” gumam Adi. “Gue harus minta maaf.”
Genta mengangguk. “Coba aja. Tapi jangan harap dia bakal nerima lu balik. Lu harus siap nerima apa pun jawabannya.”
***
Keesokan harinya, Adi kembali ke festival. Ia mencari Dinda di antara kerumunan, matanya menyapu setiap sudut. Akhirnya, ia melihatnya duduk sendirian di dekat stan makanan, memegang segelas es teh. Adi mengumpulkan keberanian, lalu berjalan mendekat.
“Dinda, boleh aku duduk?” tanyanya, suaranya bergetar.
Dinda menatapnya sejenak, lalu mengangguk tipis. “Silakan.”
Adi duduk, tangannya gelisah di atas meja. “Aku tau aku nggak pantes minta apa-apa dari kamu. Tapi aku cuma mau bilang... aku minta maaf. Aku salah banget udah ninggalin kamu. Aku takut waktu itu, aku bingung. Tapi aku nyesel, Dinda.”
Dinda menatap es teh di tangannya, jari-jarinya memutar sedotan perlahan. “Adi, aku udah denger kata-kata itu sebelumnya. Kamu bilang kamu nyesel, tapi kamu tetep pergi. Aku capek, aku nggak mau balik ke situ lagi.”
Adi merasa dadanya semakin sesak. “Aku janji, aku udah berubah. Aku mau balik, Dinda. Aku mau kita coba lagi.”
Dinda menggeleng pelan. “Terlambat, Adi. Aku udah punya pacar sekarang. Dia baik sama aku, dia nggak ninggalin aku kayak kamu.”
Adi membeku. “Siapa?”
Dinda menoleh ke arah kerumunan. “Dia namanya Rian. Dia lagi ngambil makan buat kami.” Sesaat kemudian, seorang lelaki tinggi dengan senyum ramah muncul, membawa dua porsi sate ayam. Ia tersenyum pada Dinda, lalu melirik Adi dengan tatapan penuh tanya.
“Oh, ini Adi,” kata Dinda pada Rian. “Teman lama.”
Rian mengangguk sopan. “Hai.. Salam kenal.”
Adi memaksakan senyum, meski hatinya terasa hancur. “Hai. Salam kenal juga.” Ia melihat cara Rian meletakkan piring di depan Dinda, cara ia tertawa kecil saat Dinda mengeluh satenya terlalu pedas. Adi tahu, Rian adalah seseorang yang lebih baik daripada dirinya.
“Aku senang kamu bahagia, Nda,” kata Adi akhirnya, suaranya parau. “Aku cuma mau bilang itu.”
Dinda tersenyum tipis, pertama kalinya malam itu. “Makasih, Di. Aku harap kamu juga bisa bahagia.”
Adi bangkit, kakinya terasa berat. “Selamat tinggal, Dinda.”
Ia berjalan menjauh, suara musik dari panggung terdengar samar di telinganya. Lirik lagu yang diputar seolah mengejeknya. Adi mengusap matanya yang mulai basah, tersenyum pahit. Mungkin memang begini akhirnya—ia harus belajar melepaskan, belajar menjadi lebih baik, meski itu berarti kehilangan Dinda selamanya.