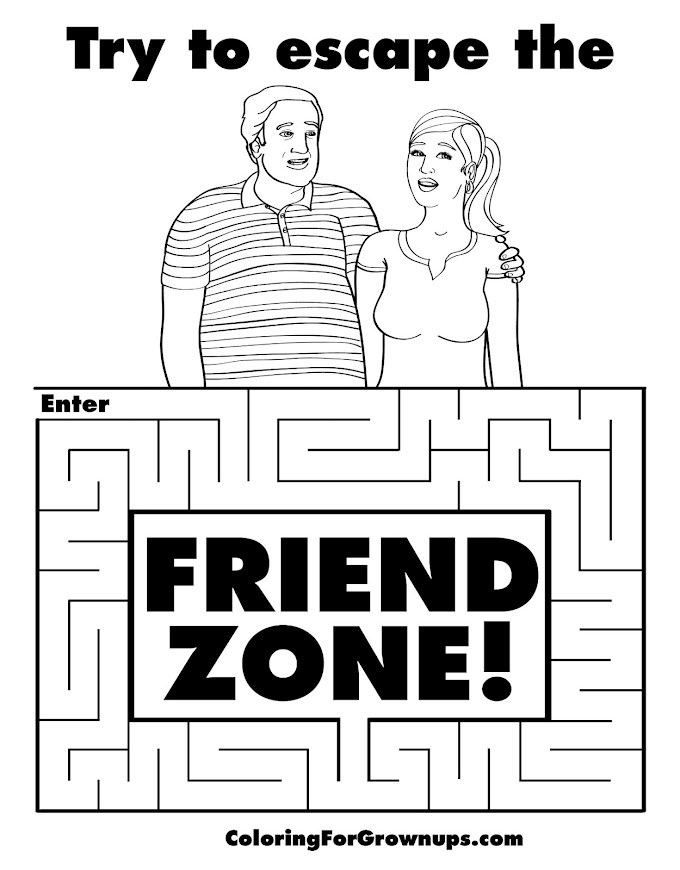Ilustrasi laut.
(Sumber gambar: freepik.com)
Rina duduk di tepi pantai, kakinya diguyur ombak kecil yang datang dan pergi, seperti napas laut yang tak pernah lelah. Matanya menatap cakrawala, tempat langit dan air bertemu dalam pelukan senja yang jingga. Angin membawa aroma garam dan bisikan halus, seolah laut berbicara padanya—dan memang begitu. Orang-orang desa Karang Sari menyebutnya "Anak Laut," tapi bagi Rina, kemampuan itu lebih seperti kutukan. Setiap sore, ia datang ke sini, mencari jawaban yang tak pernah benar-benar ia temukan, sambil memeluk luka yang tak terucap di hatinya.
Desa Karang Sari adalah tempat kecil di pesisir, tersembunyi di antara karang dan hutan bakau. Nelayan-nelayan menghabiskan hari mereka di laut, sementara angin membawa cerita-cerita lama tentang makhluk gaib dan rahasia yang tersimpan di kedalaman. Rina lahir di desa ini, tapi ia tidak pernah merasa menjadi bagian darinya. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya hilang dalam badai besar bertahun-tahun lalu. Neneknya yang membesarkannya kini terbaring lemah, meninggalkan Rina dengan kesendirian yang semakin dalam. Ia bisa mendengar laut bernyanyi, merasakan amarahnya, bahkan melihat kilasan masa depan di ombak yang bergulung. Tapi apa gunanya semua itu jika ia hanya merasa seperti bayangan di antara orang-orang yang tak memahaminya?
Kehidupan Rina berubah ketika Reza tiba di desa. Lelaki itu datang dari kota besar, membawa buku-buku tebal dan alat-alat aneh untuk meneliti laut. Ia menyewa rumah kecil tak jauh dari pantai, dan tak lama kemudian, ia mulai muncul di tempat Rina biasa duduk. Pertama kali Reza menyapanya, Rina hanya menjawab singkat, matanya tetap tertuju pada laut. Tapi Reza tidak menyerah. Hari demi hari, ia datang, duduk di sampingnya, kadang bertanya tentang desa, kadang hanya diam menikmati senja. Ada kehangatan pada sikapnya, sesuatu yang membuat Rina merasa terganggu sekaligus penasaran.
"Kenapa kamu terus datang?" tanya Rina suatu sore, nadanya tajam tapi matanya penuh keraguan.
Reza tersenyum, memandang laut yang mulai gelap. "Karena aku suka pemandangan ini. Dan aku suka melihatmu di sini."
Rina mengerutkan kening, tak tahu harus menjawab apa. Ia bangkit dan pergi, tapi kata-kata Reza terus bergema di pikirannya. Malam itu, saat bulan purnama menerangi laut dengan cahaya perak, Rina kembali ke pantai. Reza sudah ada di sana, berdiri dengan tangan di saku, menatap air yang berkilauan.
"Kamu bilang aku istimewa," kata Rina, suaranya pelan tapi tegas. "Tapi kamu tidak tahu apa-apa tentangku."
Reza menoleh, matanya penuh perhatian. "Aku tahu cukup untuk ingin tetap di sini. Ceritakan padaku, Rina. Aku ingin mengerti."
Rina menarik napas dalam-dalam. "Aku bisa berbicara dengan laut. Aku bisa mendengarnya, merasakannya. Tapi itu tidak membuatku istimewa. Itu membuatku berbeda. Dan berbeda itu menyakitkan."
Reza melangkah mendekat, tapi Rina mundur. "Kamu tidak rusak, Rina. Kamu hanya... manusia."
Air mata menggenang di mata Rina. "Kamu tidak tahu apa yang pernah aku lakukan. Aku tidak pantas untuk siapa pun."
Ia berbalik dan berlari, meninggalkan Reza dengan pertanyaan yang menggantung. Malam itu, laut bergolak lebih keras dari biasanya, seolah mencerminkan gejolak di hati Rina.
***
Keesokan harinya, angin membawa kabar buruk. Badai besar akan datang, lebih ganas dari yang pernah dilihat desa dalam bertahun-tahun. Nelayan-nelayan bergegas menarik perahu, dan warga desa memaku kayu di jendela mereka. Rina merasakan kemarahan laut sebelum orang lain menyadarinya. Ombak yang biasanya lembut kini menghantam karang dengan ganas, dan angin menderu seperti jeritan. Ia tahu ini bukan badai biasa—ada sesuatu yang salah, dan itu ada hubungannya dengannya.
Malam itu, saat langit gelap dipenuhi petir, Rina pergi ke pantai sendirian. Ia berdiri di tepi air, rambutnya diterpa angin kencang. "Apa yang kamu inginkan dariku?" bisiknya, dan suara laut menjawab di kepalanya, dalam dan bergema.
"Kamu menyangkal dirimu sendiri, Anak Laut. Kamu menolak cinta, dan aku merasakannya."
Rina terpaku. "Cinta? Aku tidak mengerti."
Tapi suara itu lenyap, dan badai semakin mendekat. Ia merasa kecil di hadapan kekuatan itu, tapi ia tidak bisa pergi. Saat itulah Reza muncul, wajahnya penuh kekhawatiran.
"Rina, kita harus pergi! Ini terlalu berbahaya!"
"Aku tidak bisa," jawab Rina, matanya tertuju pada laut. "Aku harus menghentikannya."
Reza memandangnya, bingung tapi teguh. "Baiklah. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu."
Mereka berdiri bersama, angin menderu di sekitar mereka. Rina menutup mata, mencoba menjangkau laut dengan pikirannya. "Tolong, berhenti," bisiknya. Tapi tidak ada jawaban, hanya gemuruh ombak yang semakin keras.
Reza meraih tangannya, dan kali ini Rina tidak menolak. Sentuhan itu hangat, seperti jangkar di tengah badai. Tiba-tiba, ia melihat kilasan masa lalunya—saat ia masih muda, saat kemarahannya tanpa sengaja membangkitkan laut dan hampir merenggut nyawa seorang nelayan. Sejak itu, ia mengunci hatinya, merasa bersalah, merasa tidak layak.
Tapi sekarang, dengan Reza di sisinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada seseorang yang tetap tinggal, yang tidak mundur meskipun ia mencoba mendorongnya pergi. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan percikan air laut.
"Aku menerima diriku," katanya pada laut, suaranya mantap meski bergetar. "Aku menerima cinta yang ada untukku."
Seolah mendengar, badai mulai mereda. Angin yang tadi mengamuk kini menjadi bisikan, dan ombak yang ganas kembali tenang. Langit terbuka, menampakkan bintang-bintang yang bersinar lembut. Rina menoleh ke Reza, napasnya tersengal tetapi hatinya ringan.
"Terima kasih," bisiknya.
Reza menariknya ke dalam pelukan, dan untuk pertama kalinya, Rina tidak menolak. Di kejauhan, laut tampak berkilauan, seolah tersenyum pada mereka. Desa Karang Sari selamat, dan Rina akhirnya menemukan kedamaian—bukan hanya dengan laut, tapi dengan dirinya sendiri.